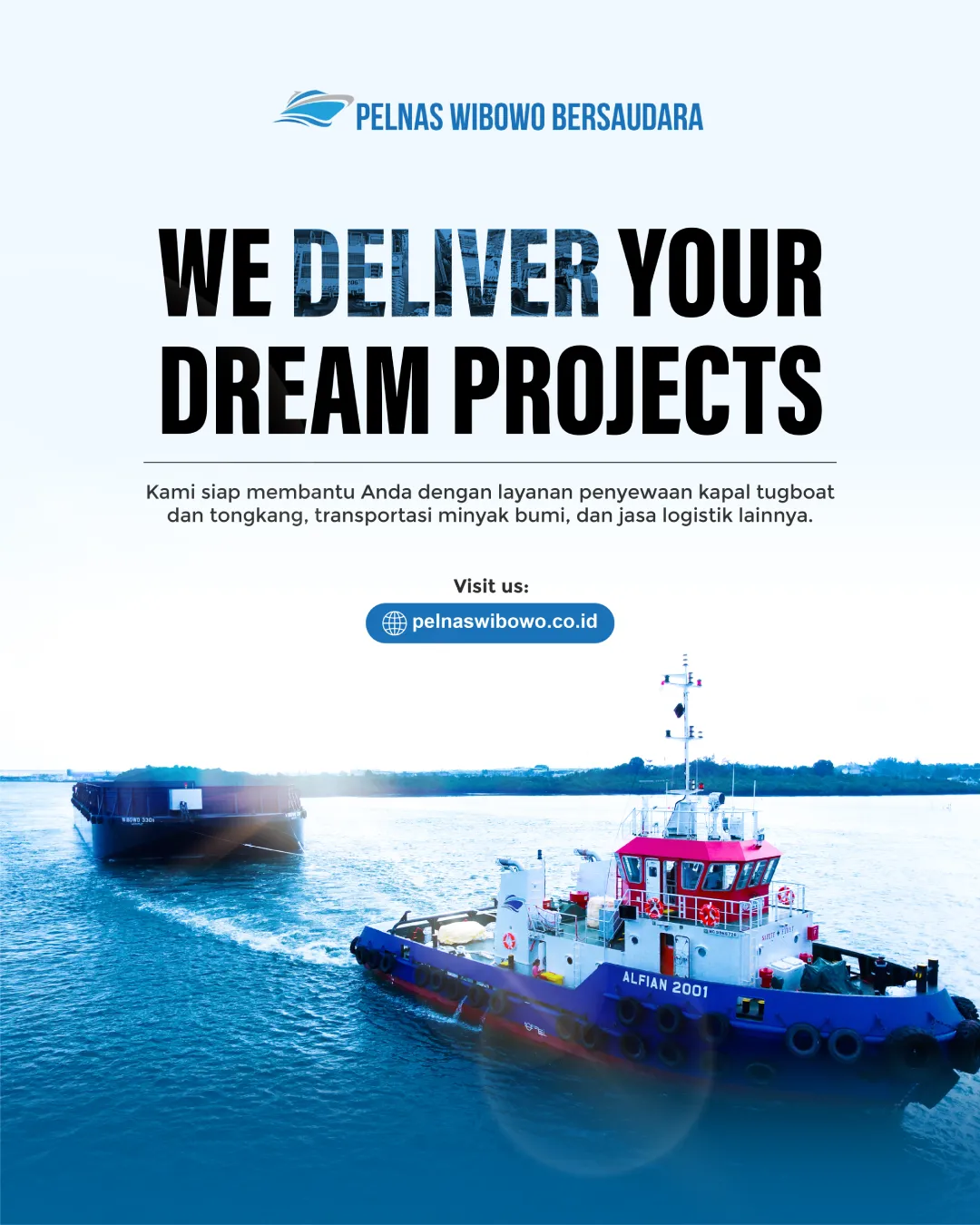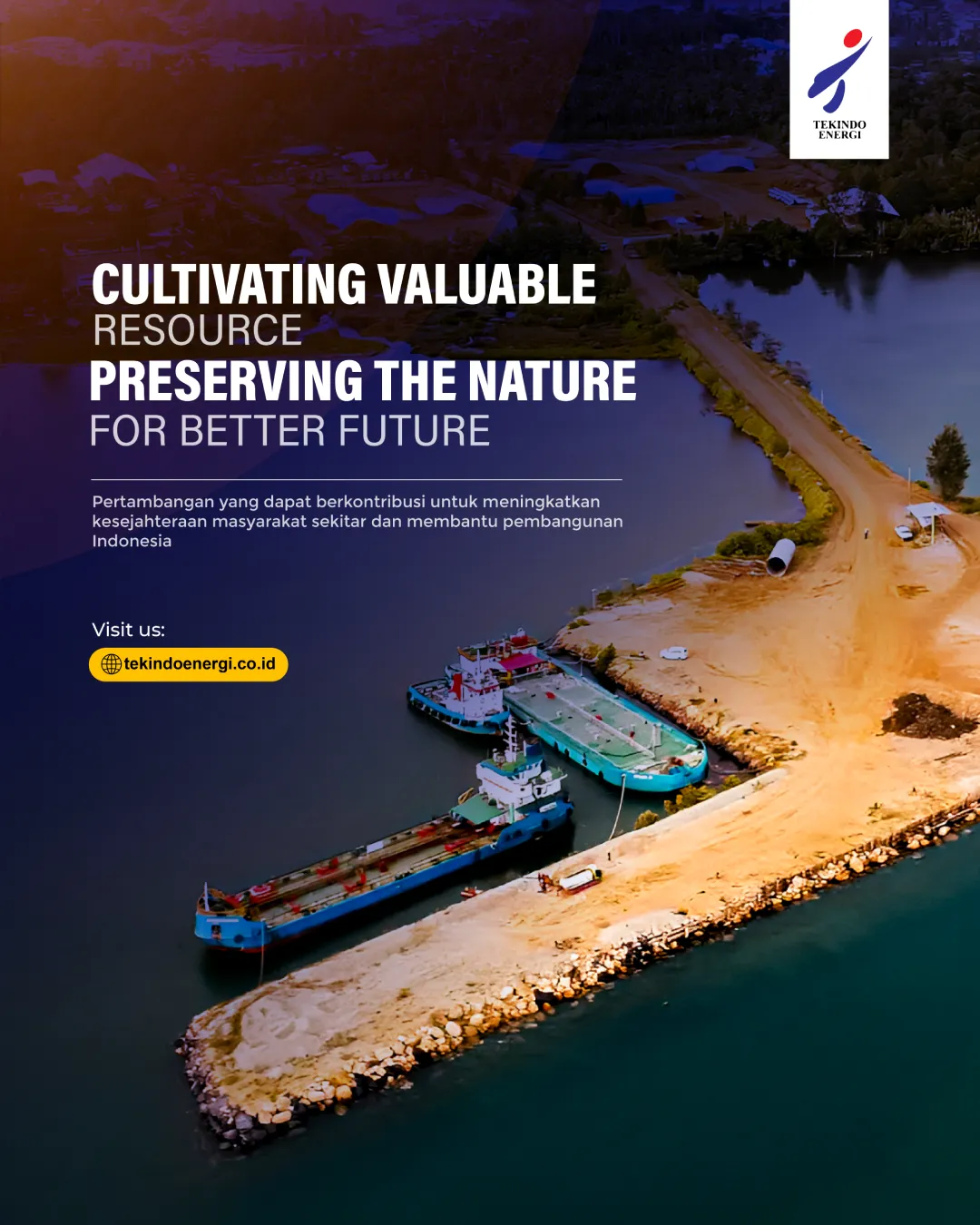BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Isu tentang jati diri dan orientasi seksual makin terbuka dibicarakan. Namun, tidak semua orang memiliki ruang aman untuk menjadi diri sendiri. Salah satu fenomena yang muncul akibat tekanan sosial dan budaya adalah lavender marriage.
Istilah ini merujuk pada pernikahan antara pria dan wanita, di mana salah satu atau bahkan keduanya memiliki orientasi seksual yang berbeda dari heteroseksual, namun memilih menikah demi memenuhi ekspektasi masyarakat.
Sejarah Singkat Lavender Marriage
Lavender marriage bukanlah fenomena baru. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-20, khususnya di Hollywood.
Kala itu, banyak selebriti yang terpaksa menikah untuk menjaga citra publik karena masyarakat belum bisa menerima keberadaan komunitas LGBTQ+.
Mereka menyembunyikan orientasi seksualnya melalui pernikahan formal demi mempertahankan karier dan reputasi.
Kerusuhan Stonewall di tahun 1969 menjadi tonggak kebangkitan komunitas LGBTQ+ dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
Namun sayangnya, hingga hari ini, lavender marriage masih terjadi terutama di negara-negara Asia, termasuk Indonesia dan India, di mana tekanan budaya dan keluarga begitu kuat.
BACA JUGA:
Skandal Dokter Oky Pratama: Dugaan Pemerasan hingga Pernikahan Palsu?
Kenapa Lavender Marriage Terjadi?
Fenomena ini muncul bukan tanpa sebab. Di banyak komunitas konservatif, identitas LGBTQ+ masih dianggap tabu.
Banyak yang takut dikucilkan, kehilangan pekerjaan, atau mempermalukan keluarga jika mereka “keluar dari lemari”.
Maka dari itu, pernikahan dengan lawan jenis menjadi cara aman untuk bertahan hidup dalam sistem yang belum ramah.
Selain untuk menyembunyikan orientasi seksual, lavender marriage juga kerap dijadikan pelindung agar individu LGBTQ+ tidak menjadi korban diskriminasi. Sayangnya, konsekuensi psikologis dari “berpura-pura” ini bisa sangat besar.
Dampak Psikologis dan Sosial
Lavender marriage bisa jadi “penyelamat wajah” di depan publik, tapi di balik pintu rumah, sering kali justru menciptakan penderitaan.
Banyak pasangan yang merasa kesepian, mengalami tekanan emosional, bahkan depresi karena harus menahan identitas sejatinya.
Lebih parah lagi, jika pasangan lawan jenis tidak mengetahui kondisi sesungguhnya. Ini bisa berujung pada konflik rumah tangga, perceraian, atau bahkan trauma berkepanjangan. Dalam beberapa kasus, pasangan merasa tertipu dan kehilangan kepercayaan diri.
Selain itu, individu dalam lavender marriage juga bisa mengalami isolasi sosial. Mereka terjebak di antara dua dunia tidak diterima sepenuhnya di komunitas heteroseksual, tapi juga terputus dari komunitas LGBTQ+ karena ketidakterbukaan.
(Hafidah Rismayanti/Budis)